Artikel:Perbandingan Pendapat Empat Mazhab dalam Masalah Aurat Perempuan dalam Kehidupan Publik
Perbandingan Pendapat Empat Mazhab dalam Masalah Aurat Perempuan dalam Kehidupan Publik
Fauzan
Nurul Hanifah
ABSTRAK
Penelitian ini membahas perbedaan pandangan empat mazhab utama dalam Islam—Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali—terkait batasan aurat perempuan dalam kehidupan publik. Permasalahan aurat perempuan kerap menjadi isu krusial dalam interaksi sosial, pendidikan, dan ruang kerja modern, yang memerlukan pemahaman hukum yang mendalam dan kontekstual. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah kitab-kitab fikih klasik serta pendapat ulama kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat mazhab memiliki kesamaan dalam hal kewajiban menutup aurat secara umum, tetapi terdapat perbedaan dalam penentuan batas minimal aurat yang boleh terlihat di ruang publik, terutama dalam situasi tertentu seperti kebutuhan darurat atau kerja profesional. Mazhab Hanafi, misalnya, membolehkan tampaknya wajah dan kedua telapak tangan, sementara mazhab Hanbali lebih cenderung mewajibkan penutupan seluruh tubuh kecuali dalam kondisi mendesak. Penelitian ini menekankan pentingnya ijtihad kontekstual agar pemahaman tentang aurat tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga relevan dengan realitas sosial perempuan Muslim masa kini.
Kata Kunci: Aurat perempuan, empat mazhab, kehidupan publik, fikih kontemporer, perbandingan hukum Islam
ABSTRACT
This research discusses the different views of the four main schools of thought in Islam – Shafi’i, Hanafi, Maliki and Hanbali – regarding the limits of women’s aurat in public life. The issue of women’s ‘awrah often becomes a crucial issue in modern social interactions, education, and workplaces, which requires a deep and contextual understanding of the law. This study uses a qualitative approach based on a literature study by examining classical fiqh books and the opinions of contemporary scholars. The results of the study show that the four madhhabs are similar in terms of the obligation to cover the aurat in general, but there are differences in determining the minimum limit of aurat that can be seen in public spaces, especially in certain situations such as emergency needs or professional work. The Hanafi school, for example, allows the appearance of the face and the palms of the hands, while the Hanbali school is more inclined to require the covering of the entire body except in urgent conditions. This research emphasizes the importance of contextual ijtihad so that the understanding of aurat is not only textual, but also relevant to the social reality of Muslim women today.
Keywords: Women’s Aurat, four madhhabs, public life, contemporary fiqh, comparative Islamic law
PENDAHULUAN
Masalah aurat perempuan merupakan topik yang selalu relevan dan menjadi perhatian utama dalam kajian hukum Islam, terutama ketika dikaitkan dengan peran perempuan di ruang publik. Dalam masyarakat modern yang semakin terbuka dan kompleks, perempuan Muslim tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga aktif dalam berbagai sektor publik seperti pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai batasan aurat yang harus dijaga oleh perempuan dalam aktivitas publik, dan bagaimana hukum Islam memposisikan hal tersebut dalam bingkai kesucian dan etika berpenampilan (Purkon, 2023).
Dalam khazanah fikih klasik, para ulama dari empat mazhab besar—Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali—telah membahas secara komprehensif mengenai batasan aurat perempuan baik dalam konteks ibadah maupun interaksi sosial. Keempat mazhab sepakat bahwa menutup aurat merupakan kewajiban syar’i, namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan batasan minimal aurat perempuan yang boleh tampak di hadapan laki-laki non-mahram, terutama dalam situasi-situasi tertentu seperti keadaan darurat atau kebutuhan profesional. Perbedaan ini berakar dari metodologi istinbath (penggalian hukum) masing-masing mazhab, termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan aurat dan hijab (Akbar, 2015).
Dalam praktiknya, pemahaman yang beragam mengenai aurat ini mempengaruhi cara berpakaian perempuan Muslim di berbagai negara dan komunitas. Ada yang mengadopsi pendapat yang longgar dengan menampakkan wajah dan telapak tangan sebagaimana mazhab Hanafi, dan ada pula yang mengikuti pandangan yang lebih ketat seperti mazhab Hanbali yang mewajibkan penutupan seluruh tubuh kecuali dalam kondisi darurat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kekayaan pendekatan hukum yang fleksibel, namun tetap berada dalam koridor syariat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pendapat-pendapat mazhab tersebut secara komparatif agar umat Islam, khususnya perempuan, dapat memahami dan memilih pendapat yang sesuai dengan konteks sosialnya tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran Islam (Sulahyuningsih et al., 2021).
Penelitian bertujuan untuk menguraikan perbedaan dan kesamaan pandangan empat mazhab besar dalam masalah aurat perempuan di ruang publik, serta menggali relevansinya dengan kondisi kehidupan perempuan Muslim masa kini. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam wacana fikih kontemporer yang bersifat kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap dinamika zaman.
METODE
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), karena fokus utama kajian ini adalah menelaah pendapat-pendapat para ulama dari empat mazhab fiqh mengenai batasan aurat perempuan dalam kehidupan publik. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik dari masing-masing mazhab seperti al-Umm karya Imam Syafi’i (Syafi’iyah), al-Muwaththa’ karya Imam Malik (Malikiyah), al-Mabsuth karya Imam al-Sarakhsi (Hanafiyah), dan al-Mughni karya Ibn Qudamah (Hanabilah), serta kitab-kitab rujukan utama lain yang menjadi otoritas dalam mazhab masing-masing.
Sumber sekunder mencakup buku-buku fiqh kontemporer, artikel ilmiah, jurnal, dan disertasi yang relevan sebagai pelengkap dan penguat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah secara sistematis isi kitab-kitab dan literatur yang membahas aurat perempuan menurut keempat mazhab. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci pendapat masing-masing mazhab, sementara analisis komparatif bertujuan untuk membandingkan argumentasi hukum serta dasar-dasar syar’i yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap variasi pandangan mazhab mengenai aurat perempuan dalam ruang publik serta relevansinya terhadap konteks kekinian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Batas Aurat Perempuan di Hadapan Non-Mahram Dalam Pandangan 4 Mazhab
Pembahasan tentang aurat perempuan merupakan bagian penting dari tata etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Aurat secara umum diartikan sebagai bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain yang bukan mahram. Keempat mazhab besar dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram, meskipun mereka sepakat bahwa perempuan harus menjaga kehormatan dan menutup sebagian besar tubuhnya di ruang public (Email, 2024).
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aurat perempuan di hadapan non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pandangan ini diambil berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Qur’an dalam Surah An-Nur ayat 31, khususnya pada frasa “kecuali yang biasa tampak darinya”. Menurut ulama Hanafiyah, wajah dan telapak tangan adalah bagian yang lazim terbuka dalam kehidupan sehari-hari dan diperlukan untuk aktivitas seperti makan, bekerja, atau berinteraksi sosial (Purkon, 2023).
Dalam praktiknya, mazhab Hanafi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Jika terbukanya wajah dapat menimbulkan fitnah, yaitu menarik perhatian atau syahwat dari laki-laki non-mahram, maka hukum membuka wajah bisa berubah menjadi makruh atau haram. Oleh sebab itu, dalam konteks sosial yang rawan fitnah, sebagian ulama Hanafiyah menyarankan agar perempuan menutup wajahnya. Namun, secara hukum dasar, wajah dan telapak tangan bukanlah aurat dalam pandangan mazhab ini (Purkon, 2023).
Mazhab Maliki memiliki pandangan yang serupa dengan Hanafi dalam hal batas minimal aurat perempuan, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, ulama Maliki lebih menekankan pentingnya konteks sosial. Dalam situasi di mana membuka wajah dan tangan berpotensi menimbulkan fitnah atau menurunkan kehormatan perempuan, maka menutupnya dianggap lebih utama, bahkan bisa menjadi wajib. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang tidak aman secara moral, mazhab Maliki cenderung mengarahkan perempuan untuk menutup wajahnya (Purkon, 2023).
Dalam sumber-sumber klasik Maliki, disebutkan bahwa wajah dan tangan bukan aurat secara mutlak, namun pembukaannya hanya dibolehkan untuk keperluan tertentu seperti bertransaksi di pasar, menjadi saksi, atau bekerja. Apabila alasan tersebut tidak mendesak, dan ada potensi godaan atau syahwat, maka pembukaan wajah dan tangan dapat menjadi perbuatan yang tidak dianjurkan (Al & Al, 2024).
Mazhab Syafi’i juga memiliki dua pandangan terkait batas aurat perempuan. Mayoritas ulama dalam mazhab ini menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pandangan ini didasarkan pada hadits-hadits shahih serta pemahaman terhadap kondisi perempuan dalam masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana perempuan tidak selalu menutup wajahnya dalam aktivitas sehari-hari (Sainul & Amanah, 2016).
Terdapat juga pendapat minoritas dalam mazhab Syafi’i yang lebih ketat, menyatakan bahwa wajah dan tangan termasuk aurat dan wajib ditutup. Pendapat ini biasanya dipilih oleh kalangan ulama yang lebih berhati-hati atau dalam konteks sosial yang dipandang lebih terbuka terhadap fitnah. Dalam praktiknya, hukum cadar dalam mazhab Syafi’i bisa diklasifikasikan sebagai wajib, sunnah, atau khilaful-awla (lebih baik ditinggalkan), tergantung pada interpretasi dan kondisi Masyarakat (Sainul & Amanah, 2016).
Syafi’i dikenal sebagai mazhab yang memiliki spektrum pendapat yang luas, sehingga perbedaan penerapan sangat mungkin terjadi antar komunitas pengikutnya. Di Asia Tenggara misalnya, banyak masyarakat Syafi’i yang tidak mewajibkan cadar, tetapi tetap menekankan pakaian longgar dan sopan (Ikhsan, 2018).
Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang paling ketat di antara empat mazhab. Dalam mazhab ini, seluruh tubuh perempuan, termasuk wajah dan telapak tangan, dianggap sebagai aurat yang wajib ditutup di hadapan laki-laki non-mahram. Pandangan ini didasarkan pada kehati-hatian dalam menjaga kesucian dan menghindari fitnah. Dalam kitab-kitab Hanbali disebutkan bahwa perempuan sebaiknya menutup seluruh tubuhnya jika keluar rumah, bahkan dalam interaksi singkat dengan laki-laki asing (Purkon, 2023).
Ada pandangan minoritas dalam Hanbali yang memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu. Misalnya, dalam kebutuhan praktis seperti shalat, jual beli, atau interaksi profesional, wajah dan tangan bisa terlihat apabila tidak menimbulkan syahwat. Namun, prinsip umumnya tetap tegas bahwa menutup seluruh tubuh adalah langkah terbaik untuk menjaga kehormatan (Yenni, 2020).
Keempat mazhab memiliki titik temu dalam prinsip dasar menjaga aurat perempuan, tetapi berbeda dalam detail aplikatif, terutama menyangkut wajah dan telapak tangan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan mayoritas Syafi’i mengizinkan terbukanya dua bagian ini dalam kondisi aman dari fitnah, sementara Hanbali cenderung mewajibkan penutupan penuh (Rahmazani, 2017).
Faktor utama yang membedakan pendapat para ulama bukan semata perbedaan dalil, tetapi juga terkait dengan pendekatan terhadap fitnah, kebutuhan masyarakat, dan tingkat kehati-hatian dalam mencegah interaksi yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan. Keempat mazhab memberikan ruang bagi pertimbangan sosial dan budaya dalam penerapan hukum aurat (Fitrotunnisa, 2018) .
Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting agar umat Islam dapat saling menghargai pilihan pakaian dan ekspresi syariah yang berbeda-beda, selama masih berada dalam kerangka dalil dan kaidah fiqih. Tidak semestinya satu pandangan memaksakan diri atas yang lain, sebab keempat mazhab memiliki legitimasi ilmiah dan historis dalam tradisi Islam (Tiara et al., 2022).
Masalah aurat perempuan dalam kehidupan publik merupakan tema yang terus menjadi perbincangan dalam diskursus hukum Islam. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga mencakup interaksi sosial, budaya, hingga wacana gender dalam masyarakat. Dalam fiqh Islam, konsep aurat diatur secara sistematis oleh para ulama dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Perbedaan dalam penetapan batasan aurat perempuan di ruang publik mencerminkan kekayaan metodologi istinbat (penarikan hukum) yang digunakan oleh masing-masing mazhab serta perbedaan konteks sosial dan budaya yang memengaruhi lahirnya pandangan mereka.
Isu mengenai aurat perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu topik yang banyak dibahas dalam khazanah fiqh Islam. Keempat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—memiliki kesamaan dalam prinsip dasar bahwa menutup aurat adalah kewajiban bagi perempuan muslimah. Namun, masing-masing mazhab berbeda dalam menetapkan batas-batas aurat perempuan, terutama ketika berada di ruang publik atau di hadapan laki-laki non-mahram.
Hukum Penggunaan Cadar dalam Kehidupan Publik di Kalangan 4 Mazhab
Cadar atau niqab adalah kain penutup wajah perempuan yang digunakan sebagai bagian dari pakaian syar’i. Dalam Islam, penggunaan cadar menjadi isu yang banyak dibahas dalam fiqih klasik dan kontemporer, terutama berkaitan dengan aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram dalam ruang publik. Meskipun semua mazhab sepakat bahwa perempuan wajib menutup sebagian besar tubuhnya, hukum cadar tidak menjadi konsensus dan menjadi objek ijtihad masing-masing mazhab (Hilmi et al., 2018).
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, sehingga perempuan tidak wajib mengenakan cadar dalam kehidupan publik. Namun, ulama Hanafi memberikan batasan penting: jika dikhawatirkan terbukanya wajah dapat menimbulkan fitnah (daya tarik yang memancing syahwat), maka mengenakan cadar menjadi wajib. Oleh sebab itu, hukum penggunaan cadar dalam mazhab Hanafi bersifat situasional: tidak wajib dalam keadaan normal, tetapi bisa berubah menjadi wajib bila ada risiko fitnah yang nyata (Fitrotunnisa, 2018).
Pendekatan Hanafi dalam hal ini cukup pragmatis. Mereka melihat kebutuhan sosial perempuan untuk berinteraksi, bekerja, dan bermuamalah sebagai alasan yang membolehkan wajah terbuka. Namun, mereka tetap menekankan bahwa pakaian perempuan harus sederhana, longgar, dan tidak menarik perhatian berlebihan. Penggunaan cadar, dalam hal ini, bukan bagian dari kewajiban pokok, melainkan tindakan preventif dalam kondisi tertentu (Ningsih & Setiawan, 2019).
Mazhab Maliki juga menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan perempuan bukan aurat, dan karena itu cadar tidak wajib dalam kehidupan publik. Akan tetapi, mazhab ini juga memberikan catatan penting bahwa dalam situasi sosial yang sarat dengan kerusakan moral atau potensi fitnah yang tinggi, maka mengenakan cadar menjadi tindakan yang dianjurkan, bahkan bisa mencapai tingkat wajib. Seperti halnya Hanafi, Maliki menekankan pentingnya konteks sosial dan kondisi masyarakat dalam menentukan hukumnya (Ilham, 2021).
Literatur Maliki, cadar dianggap sebagai langkah kehati-hatian (sadd al-dzari’ah), yaitu tindakan yang diambil untuk mencegah kerusakan atau pelanggaran syariah. Oleh sebab itu, meskipun cadar bukan kewajiban tetap dalam mazhab ini, penggunaannya tidak dianggap asing atau ekstrem, tetapi dilihat sebagai respons wajar terhadap kebutuhan menjaga kehormatan perempuan di ruang public (Andiko, 2018).
Mazhab Syafi’i memiliki keragaman pandangan yang lebih besar dalam isu cadar. Mayoritas ulama Syafi’i berpandangan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, sehingga perempuan tidak wajib mengenakan cadar. Namun, sebagian ulama dalam mazhab ini, seperti Imam Nawawi, mengemukakan bahwa dalam situasi tertentu, seperti adanya kekhawatiran fitnah, maka menutup wajah bisa menjadi wajib. Bahkan ada pendapat minoritas dalam Syafi’iyah yang menyatakan bahwa wajah dan tangan adalah aurat dan selalu wajib ditutup (Ilham, 2021).
Perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi’i menyebabkan hukum cadar dalam komunitas pengikutnya sangat bervariasi. Ada yang memandangnya sebagai kewajiban syar’i yang mutlak, ada pula yang menilainya sebagai anjuran yang kuat (sunnah muakkadah), dan ada yang hanya menganggapnya sebagai pilihan pribadi yang tidak terkait dengan hukum wajib. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Syafi’i, terutama di Asia Tenggara, memiliki praktik keagamaan yang beragam dalam hal cadar (Abdillah & Rahmattika, 2023).
Mazhab Hanbali adalah satu-satunya mazhab yang secara mayoritas menetapkan bahwa cadar adalah wajib bagi perempuan muslimah dalam kehidupan publik. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa wajah dan telapak tangan termasuk aurat, sehingga wajib ditutup di hadapan laki-laki non-mahram. Ulama besar seperti Ibnu Qudamah dan Ibn Taimiyyah membela posisi ini dengan alasan menjaga kesucian perempuan dan menutup pintu fitnah (Mubakkirah, 2020).
Hanbali menggunakan pendekatan sangat hati-hati (ihtiyath), yaitu dengan menetapkan batasan maksimal dalam menutup tubuh perempuan. Dalam praktiknya, pengikut mazhab ini mewajibkan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan bahkan terkadang mata, jika memungkinkan. Oleh karena itu, dalam komunitas Hanbali, cadar bukan sekadar pilihan atau kebiasaan budaya, melainkan bagian dari kewajiban agama yang jelas.
Meskipun mazhab Hanbali ketat, sebagian ulama Hanbali tetap mengakui adanya pengecualian dalam kondisi darurat atau kebutuhan syar’i. Misalnya, dalam kasus perempuan yang menjadi saksi di pengadilan, bekerja di luar rumah, atau dalam pelayanan medis, memperlihatkan wajah dan tangan dapat diperbolehkan bila tidak menimbulkan syahwat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ketat, mazhab ini tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan.
Keseluruhan pandangan empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ijma’ (kesepakatan bulat) mengenai kewajiban cadar dalam kehidupan publik. Mazhab Hanbali mewajibkan secara mutlak, sementara mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i mayoritas memandangnya sebagai tindakan yang tidak wajib, tetapi bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Fitnah menjadi kata kunci yang menentukan perubahan hukum dalam semua mazhab.
Perbedaan menunjukkan bahwa hukum penggunaan cadar sangat erat kaitannya dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, dalam masyarakat muslim modern, pendekatan terhadap cadar seharusnya mengedepankan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Perempuan yang mengenakan cadar tidak boleh dicela, sebagaimana perempuan yang memilih untuk tidak bercadar tidak otomatis dianggap lalai, selama pakaian mereka tetap memenuhi syarat aurat menurut syariah.
Secara keseluruhan, penggunaan cadar dalam empat mazhab adalah refleksi dari keluasan ijtihad dalam Islam. Tidak hanya menunjukkan kedalaman pemikiran hukum Islam, tetapi juga memperlihatkan fleksibilitas syariat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi zaman dan kebutuhan umat. Dalam kehidupan publik, yang terpenting adalah komitmen menjaga kesopanan, menutup aurat, dan menjauhi fitnah—baik dengan cadar maupun tanpa cadar, selama sesuai dengan kaidah masing-masing mazhab.
KESIMPULAN
Perbandingan pendapat empat mazhab dalam masalah aurat perempuan dalam kehidupan publik menunjukkan bahwa seluruh mazhab sepakat perempuan wajib menutup sebagian besar tubuhnya di hadapan laki-laki non-mahram. Namun, perbedaan utama terletak pada batas aurat wajah dan telapak tangan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan mayoritas Syafi’i sepakat bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, sehingga boleh terbuka di ruang publik selama tidak menimbulkan fitnah. Sebaliknya, mazhab Hanbali berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan termasuk wajah dan tangan adalah aurat, sehingga wajib ditutup secara menyeluruh. Keempat mazhab juga sepakat bahwa potensi fitnah menjadi faktor penting dalam perubahan hukum. Jika terbukanya wajah dan tangan dikhawatirkan mengundang syahwat atau kerusakan moral, maka semua mazhab memperbolehkan atau bahkan menganjurkan agar perempuan menutup wajahnya.
REFERENSI
Abdillah, M. T., & Rahmattika, N. (2023). Fenomena Penggunaan Cadar di Kalangan Pemudi Muslimah Banjarmasin: Identitas Sosial di Tengah Arus Tren Mode Berpakaian. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 22(2), 131–141. https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i2.10070
Akbar, E. (2015). Ta’Aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’I Dan Ja’Fari. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 14(1), 55. https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66
Al, S., & Al, M. (2024). MENDORONG INOVASI EKONOMI SYARIAH MELALUI FLEKSIBILITAS HUKUM MAZHAB HANAFI : STUDI KOMPARATIF DENGAN MAZHAB SYAFI ’ I. 1(1), 1–14.
Andiko, T. (2018). Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd al-Dzarî`ah. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 22(1), 113. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.993
Email, C. (2024). ANALISIS ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM FILM CAHAYA CINTA PESANTREN Agus Arisman Diyanto* Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Deli Serdang. V(2), 3–12.
Fitrotunnisa, S. (2018). Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah). Jurnal Penelitian Medan Agama, 9(2), 227–246. http://www.kmasjid.com.my/pdf.php?contentid=1453&type=menu
Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2), 91–102.
Ikhsan, M. (2018). Sejarah Mazhab Fikih di Asia Tenggara. Nukhbatul ’Ulum, 4(2), 20–39. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.39
Ilham, L. (2021). Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah, 6(2), 157. https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.157-182
Mubakkirah, F. (2020). MENYOROT FENOMENA CADAR DI INDONESIA Fadhliah Mubakkirah. Musawa, 12(1), 30–48.
Ningsih, R. Y., & Setiawan, D. (2019). Refleksi Penelitian Budaya Organisasi Di Indonesia. Mix Jurnal Ilmiah Manajemen, 9(3), 480. https://doi.org/10.22441/mix.2019.v9i3.007
Purkon, A. (2023). Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer. Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 9(3), 1–16.
Rahmazani. (2017). Pakaian Perempuan Dalam Pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur ( Studi Perbandingan Metode Penafsiran Alquran ). Skripsi, 21.
Sainul, S., & Amanah, N. (2016). Batas Aurat Perempuan dalam Pinangan Menurut Mazhab Zhahiri. Istinbath: Jurnal Hukum, 13(2), 361–408.
Sulahyuningsih, E., Aloysia, Y., & Alfia, D. (2021). Analysis of Harmful Traditional Practices: Female Circumcision as an Indocator of Gender Equality in The Perspective of Religion, Transcultural and Reproductive Healthin in Sumbawa District. Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, 12(1), 134–148. https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/jikk/article/view/916/586%0Ahttps://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.916
Tiara, R. A., Fakultas, M., Universtas, H., Kuala, S., Lestari, C. R., Hukum, F., & Syiah, U. (2022). Fakultas hukum universitas syiah kuala. 6(1), 36–43.
Yenni, N. Z. (2020). Tafsir Surat Al-Isra’Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin). 33. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21973/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21973/1/Nanda Zulisma Yenni%2C 150103040%2C FSH%2C PMH%2C 082278824316.pdf




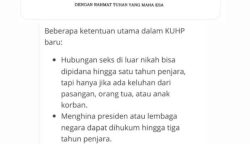

Tinggalkan Balasan